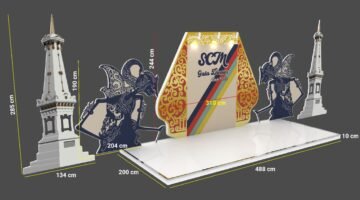Pendidikan – TeropongRakyat.co || Serombongan manusia dari bumi naik ke sorga, dan Tuhan menyambutnya, meskipun mula-mula Ia sejenak lupa geografi asal mereka— mungkin karena planet itu sudah akan segera berakhir.
Selamat datang, kata Tuhan, dan segera Ia menyeleksi siapa pantas ditempatkan di mana. Dalam “Heavenly Discourse”, kumpulan satire Charles Erskine Scott Wood yang terbit di tahun 1927 di New York — yang saya pakai mengawali tulisan ini — keputusan Tuhan begini: orang Fundamentalis akan ditaruh jauh di bawah, di lapis ke-57. Sedangkan penyair dan seniman boleh tinggal bersama Tuhan.
Termasuk Mark Twain, sastrawan humoris. “Kau di sini saja….”, kata Tuhan kepada pengarang “Huckleberry Finn” itu. “Kau akan ketemu banyak teman: Aristophanes, Rabelais, Cervantes, Shakespeare, Dickens. Aku tak tahu apa jadinya sorga tanpa penyair dan humoris….”
Tuhan, dalam “Heavenly Discourse,” tak menyukai Reformer. Jenis orang Protestan ini hendak memperbaiki akhlak manusia bila perlu dengan penjara. “Kamu nggak termasuk anggota surga”, kata Tuhan. Sebab kata Tuhan kepada sang Reformer, “kau terlalu banyak menghakimi sesamamu.” Dan itu bukan kemerdekaan; “padahal kemerdekaan adalah akidah pertama sorga.”
Maka hari itu dikeluarkanlah semua yang menghadap, kecuali ilmuwan, seniman, penyair, dan Mark Twain…
“Heavenly Discourse” bermula sebagai tulisan di majalah “the Masses.” Berkala ini sebuah media progresif, antiperang, anti ketimpangan sosial. Sebagai kumpulan, buku ini tak terasa punya kesatuan. Yang menonjol adalah keberaniannya dituduh melecehkan Tuhan dan hal-hal suci yang lain — meskipun, jika disimak dari petilan di atas, Tuhan ditampilkan dalam wajah yang simpatik, bukan pencemburu, pendendam, dan menakutkan. Kesan Mark Twain: “Dia nggak jelek-jelek amat. Sama sekali nggak jelek seperti yang sering diceritakan.”
Tuhan tak menyebalkan, dalam pandangan Wood, karena menghargai yang lucu. Saya tak tahu dari mana Wood mendapatkan perspektif itu. Yang tercatat, lulusan akademi militer West Point tahun 1874 ini, yang terlibat peperangan menaklukkan suku-suku Indian, kemudian dikenal sebagai seorang yang menentang kekerasan. Ia seorang anarkis dalam arti yang damai: seorang seniman (ia juga melukis) yang tak menyukai kekuasaan Negara.
Bisa kita pahami kenapa Tuhannya bukan Maha Kuasa, melainkan Maha Santai. Doktrin agama yang serba melarang, puritan, dan kaku adalah antithesis bagi Tuhan dalam “theologi” Wood.
Wood mendahului Umberto Eco dalam novel “Il nome de la Rosa,” yang menggambarkan pertentangan antara ketawa dan iman. Jorge, kepala biara yang streng dan kaku, yakin bahwa Yesus tak pernah ketawa. Maka padri itu mencegah, dengan jebakan kematian, biarawan yang masuk ke dalam perpustakaan untuk membaca kitab tentang humor.
Orang-orang yang taat beragama cenderung gamang kepada lelucon. Mereka mengutamakan tradisi, kepastian, dan konformitas. Mereka waswas kepada pikiran dan perilaku yang tercetus spontan, pandangan yang ambigu, hal-hal yang mengejutkan karena aneh. Agama, terutama yang telah jadi lembaga yang dijaga hukum-hukum, mendapatkan strukturnya — seperti sebuah piramida — karena kebutuhan akan kesatu-paduan. Iman menentukannya.
Sebaliknya, humor mencerai-beraikan struktur. Dalam pentas Srimulat sering ditampilkan seorang majikan duduk atau bebicara dengan pelayannya, tapi segera, hierarki mereka dikacau-balaukan. Film “Inglourious Basterds” karya Quentin Tarantino bukan saja menampilkan ejaan Inggris yang tanpa gramar dan usaha berbahasa Italia yang ngawur, tapi juga cerita dari Perang Dunia II yang nekad menyimpang dari sejarah.
Bercanda mengandung sikap main-main. Yang kocak bisa berarti nyrempet-nyrempet bahaya — bahkan risiko cidera fisik. Film-film dengan unsur slapstick — seperti Harold Lloyd dalam “Safety Last” di tahun 1923 yang memanjat tembok tinggi dengan mengenakan jas dan dasi — menggabungkan yang mendebarkan dengan yang menggelikan.
Smentara itu, agama bersungguh-sungguh dengan kontrol. Sembahyang lima waktu, ke gereja tiap hari Minggu, dengan khotbah yang tak henti-hentinya menganjurkan pengendalian diri: metode yang menjadikan ibadah kebiasaan. Kalaupun hasilnya bukan penghayatan yang bebas, itu lebih dipujikan ketimbang ketawa keras. Di abad ke 4, Santo Basilius Caesaria menegaskan: “Ketawa yang terbahak-bahak, dengan tubuh terguncang-guncang tanpa kendali, tak menunjukkan jiwa yang tertib, tak juga martabat atau kemampuan menguasai diri”.
Yang tak dilihat sang santo: humor bisa membuat jiwa lebih terbuka, sedangkan ketaatan kepada agama sering membuat sikap tertutup. Yang ganjil, yang menyimpang, cenderung dicurigai.
Tapi tak hanya oleh agama; lebih tepat, oleh tiap otoritas dan kekuasaan yang menghendaki orang pantas jadi manusia karena taat. Milan Kundera, sastrawan yang hidup di bawah rezim Stalinis di Cekoslowakia, mengenal nilai humor dalam tekanan politik zamannya. Ia bisa mengenali seseorang bukan seorang penganut Stalin dari kemampuannya ketawa. Seorang yang suka ketawa dan mampu mengetawaan diri sendiri adalah orang yang mempercayai orang lain. Tanpa paranoia dan dugaan konspirasi. Hidup bebrayan bisa menyenangkan. Ada sikap menikmati hari ini, menolak untuk menganggap serius tujuan sosialisme, atau janji sorga kelak. Humor bisa mematahkan dengan satu pukulan setiap pretensi serba lurus, serba benar, serba suci.
Sebab itu, para pemegang ideologi dan kekuasaan totaliter, yang hendak menggerakkan manusia dengan mengubah secara total lahir batinnya, mencoba menyetop humor. Dalam novel “1984” George Orwell, jurubicara partai yang memerintah dengan doktrin dan tangan besi mengatakan: “Di masa depan yang ideal, tak ada ketawa, kecuali ketawa kemenangan atas musuh yang ditaklukkan.”
Tuhan dalam satire “Heavenly Discourse” tidak demikian. Alhamdulillah.
Penulis : Romli S.IP
Editor : Romli S.IP
Sumber Berita: #GM /Arsip Pribadi / https://teropongrakyat.co/tuhan-ketawa/