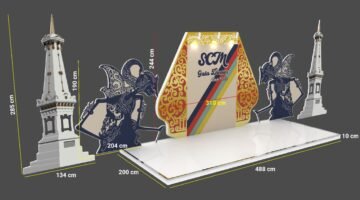Oleh: Johan Sopaheluwakan, S.Pd., C.EJ., C.BJ.
Jakarta – Teropongrakyat.co – 5 September 2025 – Keputusan kontroversial Polri dalam sidang etik terkait kasus anggota Brimob yang diduga “melindas warga” memicu perdebatan sengit. Apakah ini bukti bahwa supremasi hukum di Indonesia telah tumbang di bawah tekanan opini publik?
Pemecatan Kompol Cosmas dkk, yang diumumkan dengan dalih keberpihakan pada rakyat, justru mengundang kecurigaan. Mungkinkah keputusan ini diambil bukan berdasarkan fakta operasional di lapangan, melainkan karena derasnya gelombang opini publik yang menghakimi?
Indonesia seolah tak asing dengan fenomena penghakiman oleh publik. Sejak dulu, “tekanan massa dan opini liar” kerap menjadi alat pemaksa bagi para pengambil keputusan. Kini, gerakan ini menjelma menjadi alat penekan yang memaksa institusi seperti aparat keamanan, lembaga peradilan, atau pemerintah untuk tunduk pada keinginan sekelompok orang.
Beberapa tahun terakhir, fenomena ini semakin mengkhawatirkan. Pengarahan massa, baik sporadis maupun terorganisir, digunakan sebagai alat penekan dalam pengambilan keputusan politik dan peradilan. Ironisnya, pengerahan massa ini sering kali berlandaskan pada kesamaan profesi, ideologi, agama, etnis, atau suku. Gerakan-gerakan ini, yang seringkali disebut sebagai aksi demonstrasi, pada dasarnya adalah bentuk lain dari gerakan politik yang bertujuan untuk menenggelamkan supremasi hukum.
Tujuan utama dari politik supremasi tekanan massa dan opini publik yang liar adalah memaksa institusi hukum dan politik untuk melanggar, melawan, atau meniadakan undang-undang yang berlaku, demi memenuhi keinginan kelompok penekan.
Jika fenomena ini terus dibiarkan, dampaknya akan sangat berbahaya. Keputusan hukum dan politik tidak lagi didasarkan pada aturan yang berlaku, tetapi pada tuntutan massa. Masyarakat akan terkoyak-koyak, menimbulkan luka batin yang sulit disembuhkan, serta memicu kebencian dan dendam politik. Pengerahan massa berbasis identitas juga akan memperlebar jurang akibat sentimen SARA.
Perkembangan media sosial justru memperkuat fenomena ini. Opini publik yang dulu terbatas dan bergerak lambat, kini dapat menyebar dengan kecepatan kilat, menciptakan gelombang tekanan yang masif dalam hitungan jam. Informasi yang belum terverifikasi, potongan video yang tidak utuh, atau narasi yang memancing emosi bisa dengan mudah menjadi “fakta” di ruang digital.
Akibatnya, institusi seperti Polri berada di posisi sulit. Mereka dihadapkan pada dua pilihan: menegakkan prosedur dan fakta, atau merespons tuntutan publik demi menjaga citra dan stabilitas.
Dalam kasus Kompol Cosmas dkk, pemecatan yang cepat tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai proses hukum yang adil. Apakah ada penyelidikan mendalam tentang kondisi saat itu, termasuk prosedur operasional standar (SOP) dan apakah ia menjalankan tugas sesuai arahan? Bagaimana dengan haknya untuk membela diri di hadapan fakta yang utuh, bukan sekadar opini yang beredar di media sosial?
Fenomena ini juga menghadirkan paradoks. Di satu sisi, kontrol publik adalah bagian esensial dari demokrasi. Masyarakat harus dapat mengawasi dan mengkritik kinerja institusi negara. Namun, di sisi lain, jika pengawasan tersebut berubah menjadi penghakiman yang memaksakan kehendak, maka yang terjadi bukanlah koreksi, melainkan anarkisme yang terselubung.
Kasus pemecatan anggota Brimob oleh Polri, yang disinyalir lebih didasari pada tekanan publik daripada pertimbangan faktual, adalah cerminan nyata dari bahaya ini. Polri, dalam hal ini, lebih memilih “menyelamatkan muka” di hadapan publik, daripada tegak lurus pada fakta dan prosedur operasional. Oleh sebab itu, kita harus kembali pada prinsip-prinsip dasar negara hukum. Keputusan politik dan hukum harus didasarkan pada fakta, keadilan, dan undang-undang yang berlaku, bukan pada suara massa yang bergejolak. Media dan masyarakat harus memainkan peran yang lebih bertanggung jawab, yaitu dengan menyajikan dan mencari informasi yang berimbang, bukan sekadar menyebarkan narasi yang memancing emosi. Dengan begitu, kita dapat memastikan bahwa hukum benar-benar menjadi panglima, bukan sebaliknya.

Penulis adalah Mahasiswa Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPBJJ UT Jakarta.

Pendiri Perhimpunan Penulis dan Editor Indonesia (PENA), tinggal di Jakarta